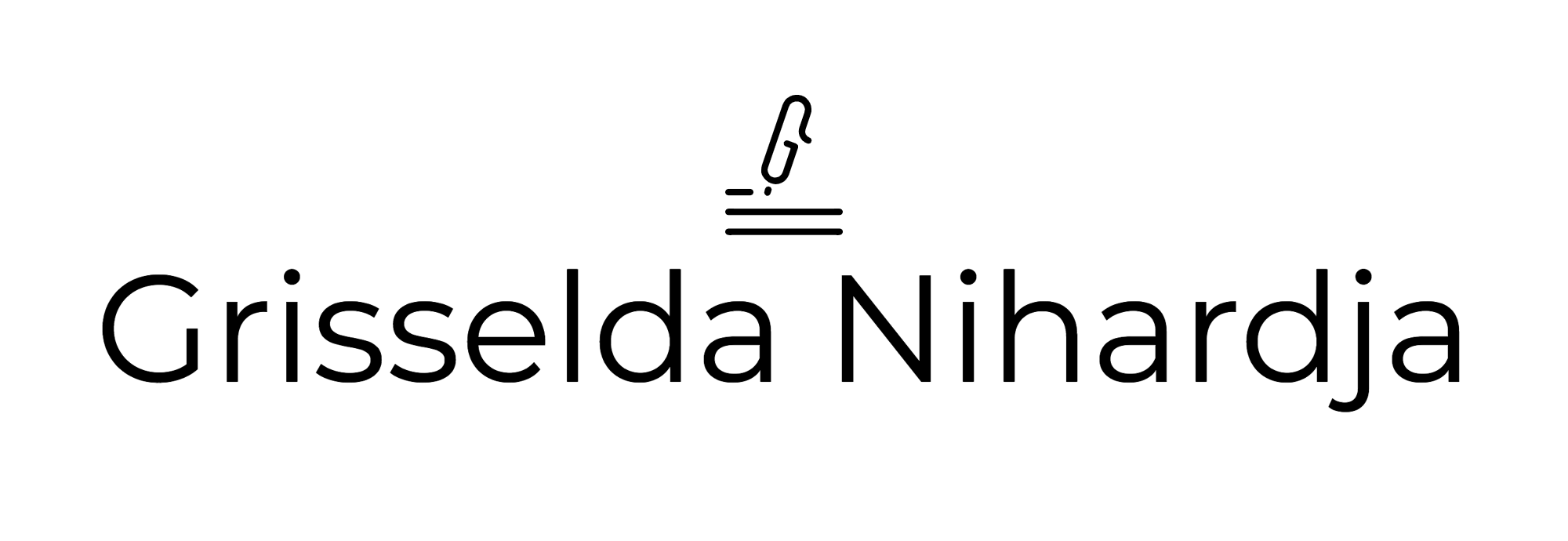Merasa Punya Utang Budi ke Penulis yang Satu Ini
Tiap pembaca punya pengalaman yang unik dengan buku. Beberapa orang bisa membaca satu buku yang sama, tapi masing-masing bisa punya kesan yang berbeda. Saking personalnya pengalaman membaca seseorang, saat ditanya siapa penulis favorit yang meninggalkan kesan lebih—lebih dalam, lebih diingat, lebih membekas—jawabannya mungkin akan beragam.
Kalau membayangkan bisa bertemu langsung dengan satu penulis, saya akan memilih Mark Manson.
Sebelum ketemu The Subtle Art of Not Giving a F*ck tahun 2017, saya hanya membaca buku fiksi. Jarang sekali baca buku non-fiksi, karena image-nya di mata saya seperti banyak omong (teori doang), motivasi yang bertele-tele (kayak kotbah), nggak practical (susah, dan contoh yang diambil cherry pick), dan halu (positivity overdose).
Namun, kesiengan membeli buku oranye ini malah “membuka mata”, dan bikin saya ketagihan baca buku non-fiksi, yang masih berlanjut, dan belum ada tanda-tanda akan bosan.
Saya sadar betul salah satu alasan suka dengan tulisan Mark Manson adalah dia nggak mengemas pesannya dengan positivity. Malah, salah satu image The Subtle Art of Not Giving a F*ck adalah buku self-help buat yang nggak suka baca buku self-help. Hahahaha.
Di salah satu wawancaranya dengan media daring Australia, Manson menyebutkan kalau positif yang ada di industri self-help agak delusional, dan bukunya adalah antidote yang mau dia sediakan. “I very much wanted to provide an antidote to that, to be a counterbalance to all the positivity and create like a negative form of self-improvement.”
I couldn’t agree more. Too much positivity is not healthy in my dictionary. Manusia skeptis seperti saya, langsung klik dengan tulisan Manson dari bab pertama.
Our culture today is obsessively focused on unrealistically positive expectations: Be happier. Be healthier. Be the best, better than the rest. Be smarter, faster, richer, sexier, more popular, more productive, more envied, and more admired.
The desire for more positive experience is itself a negative experience. And, paradoxically, the acceptance of one’s negative experience is itself a positive experience.
Baca bab duanya, makin-makin.
…, negative emotions are a call to action. When you feel them, it’s because you’re supposed to do something. Positive emotions, on the other hand, are rewards for taking the proper action.
Everything is F*cked, buku keduanya terasa sebagai panggilan, ajakan sekaligus sindirian. Lagi-lagi, saya cocok dengan caranya meramu, mengkurasi, dan memformulasikan pemikirannya dalam kata-kata. Di sini dia bahkan mengkritik “the pursuit of happiness” yang sering jadi ultimate value sejuta umat di bumi.
The pursuit of happiness is a toxic value that has long defined our culture. It is self-defeating and misleading. Living well does not mean avoiding suffering; it means suffering for the right reasons. Because if we’re going to be forced to suffer by simply existing, we might as well learn how to suffer well.
Interpretasinya atas antifragile Om Taleb juga menarik:
The human mind operates on the same principle. It can be fragile or antifragile depending on how you use it. When struck by chaos and disorder, our minds set to work making sense of it all, deducing principles and constructing mental models, predicting future events and evaluating the past. This is called “learning, and it makes us better; it allows us to gain from failure and disorder.
But when we avoid pain, when we avoid stress and chaos and tragedy and disorder, we become fragile. Our tolerance for day-to-day setbacks diminishes, and our life must shrink accordingly for us to engage only in the little bit of the world we can handle at one time.
2017 jadi tahun saya bertemu dengan buku Mark Manson. Saat itu belum ada klub buku seramai sekarang. Kalau ada pun, saya belum terpikir untuk bergabung ke komunitas apa pun. Tahun itu, kalau diingat-ingat lagi, hidup saya cuma diisi dengan kerja, pacaran, kerja, pacaran. Menyenangkan memang, tapi sekarang saat menengok ke belakang: Wow, Griss. Hari-hari dan isi kepalamu hanya dipenuhi dengan hal-hal yang ada di dalam rutinitas saja, ya.
I realized that I lacked awareness of so many things. Tidak peduli, dan tidak tahu kalau di luar bubble itu ada banyak sekali hal yang belum saya tahu. Banyak aspek dalam hidup (personal, profesional, keluarga) yang bisa dibenahi. Ada pandangan lain di luar suara yang sehari-hari terdengar, dan ada mindset baru yang bisa saya adopsi, atau setidaknya layak untuk dipertimbangkan.
Apa yang ditulis Mark Manson jadi pemantik yang bikin saya pelan-pelan memupuk rasa penasaran, keluar dari bubble, dan membiasakan diri bertemu dengan sudut pandang yang berbeda, bahkan berhadapan dengan pendapat lain yang bertentangan dengan apa yang selama ini saya anggap paling benar. “Gelas” saya yang kosong, pelan-pelan mulai terisi dari bukunya, sekaligus buku-buku non-fiksi lain yang akhirnya saya baca setelahnya.
Jadi kalau membayangkan mendapat kesempatan bertemu langsung dengan satu penulis, saya akan memilih Mark Manson. Without a doubt. Rasanya seperti punya utang budi seumur hidup ke Mark Manson. His book is the game-changer for me.
Kalau ketemu pun, bukan untuk bertanya, bukan untuk di-interview dia juga, tapi untuk bilang terima kasih.
Terima kasih sudah meruntuhkan image buku non-fiksi yang membosankan dan delusional.
Terima kasih sudah menunjukkan kalau buku non-fiksi ternyata menarik untuk dibaca.
Yang mau icip tulisannya Mark Manson, ini beberapa artikel ada di situsnya. Monggo dijajal.