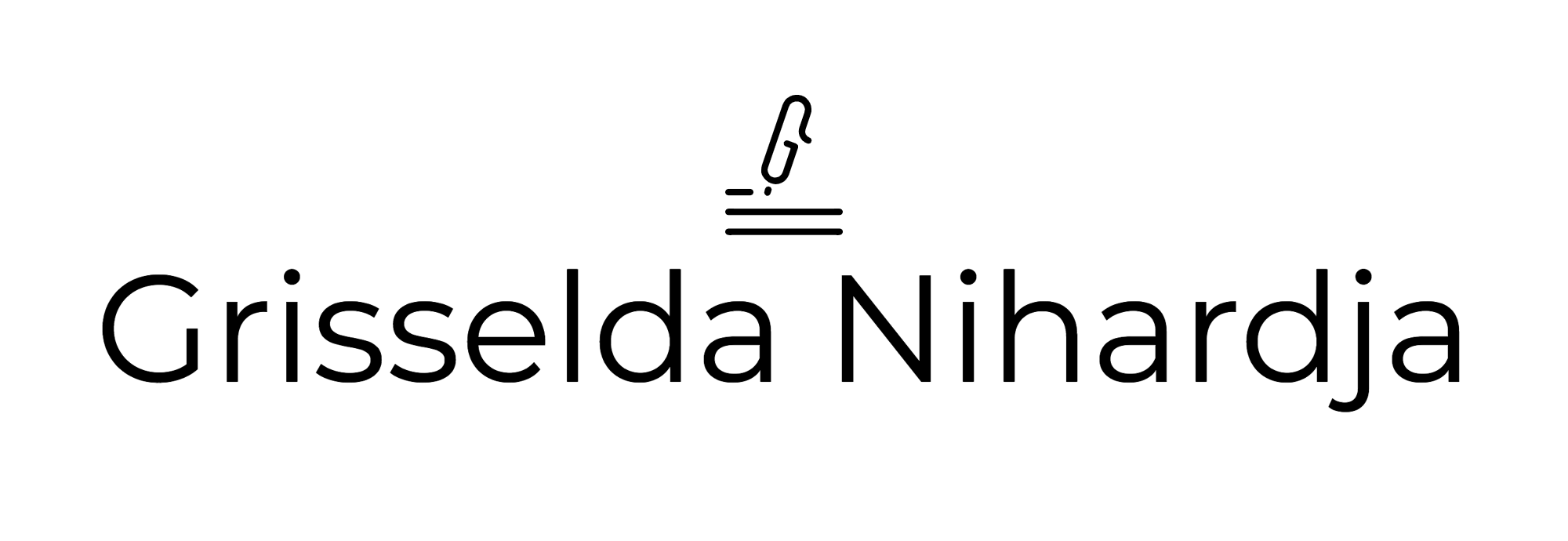Menormalisasikan "DNF"
“Aduh, gue kurang menikmati sih baca buku ini, tapi kalau nggak diselesaiin sayang, kan udah dibeli.”
Saya pun dulu begitu. Suka nggak suka, karena buku udah dibeli, otomatis jadi seperti pasang target. Pokoknya buku ini harus diselesaikan. Kan udah keluar sekian puluh/ratus ribu. Kalau nggak selesai baca, mubadzir kan uangnya? Masa DNF?
Buat yang belum tahu, di dunia perbukuan ada istilah DNF (did not finish) yang masih jadi momok untuk sebagian pembaca. Ada pembaca yang bisa DNF bukunya dengan santai, tapi ada juga pembaca yang merasa bersalah kalau nggak selesai membaca satu buku. Sayang. Sayang uangnya. Sayang udah nungguin buku ini sampai sebulan.
Apakah layak disayang-sayang?
Perbuatan “nyayang-nyayang” sesuatu yang semestinya nggak perlu disayang lagi ini ada namanya: Sunk cost fallacy. Perilaku manusia yang cenderung meneruskan sesuatu karena merasa udah menginvestasikan uang, waktu, dan tenaga, walaupun udah banyak rugi daripada untungnya.
Hesti juga pernah bahas sunk cost trap di akun bacabareng.sbc, and I couldn’t agree more. Nggak cuma pebisnis atau investor yang mengalami. Orang yang tetap stay di meh job, bad relationship, dan kita sebagai pembaca juga bisa kena sunk cost fallacy.
“We overvalue these sunk costs, we’re less willing to give them up and we are more likely to dig ourselves deeper into a hole.”
- Dan Ariely & Jeff Kreisler (Dollars and Sense)
Pemahaman yang membantu saya supaya bisa lepas dari jebakan ini adalah: Sunk cost nggak bisa kembali. Uang, tenaga, dan energi yang udah saya keluarkan nggak bisa diminta balik.
Misalnya, saya beli buku impor seharga Rp250.000. Mencoba baca tiga bab, kok nggak nikmat ya? Nggak ada geregetnya. Nggak menarik? Gaya penulisannya pun nggak cocok dengan selera. Kalau fiksi, ini karakternya kok nggak masuk akal tingkah lakunya? Plotnya kok banyak “bolongnya”? Oke, coba skip beberapa bab dan langsung ke bagian tengah, etapi masih hambar juga tuh. Kalau kena sunk cost fallacy, saya bakal merasa sayang karena udah keluar uang Rp250.000 dan jadi memaksa diri untuk membaca semua halaman buku itu. Dengan kata lain, saya jadi menghabiskan beberapa hari dan sekian jam bersama buku yang saya nggak suka.
Pertanyaannya, apakah dengan saya membaca buku itu sampai selesai lantas Rp250.000 saya bisa kembali? Tentu tidak. If an amount is spent, it’s spent. Mau saya hafalkan isi bukunya sampai ngelotok di luar kepala pun, Rp250.000 saya udah melayang.
Jadi, apakah masih perlu disayang-sayang?
Selalu ada alternatif
Anggaplah saya membutuhkan tiga hari untuk menyelesaikan satu buku. Kalau bukunya nggak bisa dinikmati, anggap jadi enam hari (dobel, kan lebih tersiksa karena nggak suka). Enam hari dipakai untuk membaca satu buku. Padahal, enam hari itu bisa digunakan untuk melakukan hal lain yang saya suka, yang lebih ada manfaatnya. That’s opportunity cost.
“Opportunity costs are alternatives. They are the things that we give away, now or later, in order to do something. These are the opportunities that we sacrifice when we make a choice.”
- Dan Ariely & Jeff Kreisler (Dollars and Sense)
Ayo kita main berandai-andai lagi. Apa yang bisa saya lakukan dengan enam hari?
Ngerjain side project → Nambah pemasukan.
Baca buku lain yang lebih jelas apa faedahnya untuk mengasah atau menambah pemahaman dan skill → bikin kerjaan makin lancar dan bisa gas pol bikin ini itu.
Nonton drakor → dapat hiburan.
Ikutan kursus atau online class yang saya suka → mengembangkan skill baru.
Latihan skill baru (edit video misalnya) → makin jago bikin video.
Sekarang dengan alternatif yang lebih tampak ini, ayo bandingkan. Enam hari dipakai untuk baca buku yang wadidaw atau enam hari dipakai untuk melakukan satu/beberapa alternatif yang sebenarnya ada? Saya jelas pilih alternatifnya :)